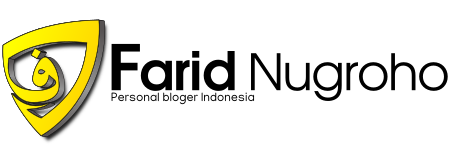Brrr, malam semakin gelap masih bersantai di LDR coffee sambil menunggu hujan agak reda, menulis sedikit hal yang sempat dibicarakan dengan sang empunya warung kopi Lidah Rakyat. Sebenarnya banyak, tapi cukup yang sederhana saja dulu yang ditulis di sini. Kalau tentang pasar tradisional, dulu pernah saya tulis. Kali ini tentang kaki lima.
 |
| Bersama Mas Oliver |
Pernahkah kita berfikir mengapa ada pedagang yang disebut dengan pedagang kaki lima? Mengenai jawabannya, saya teringat dengan acara bedah buku "Kota di Djawa Tempo Doeloe" yang disampaikan oleh penulisnya langsung yaitu Oliver Johannes Raap, dahulu setiap rumah yang ada di tepi jalan harus menyediakan area sejauh lima kaki dari rumah ke jalan. Satu kaki kurang lebih adalah 0.3 meter. Jadi, jarak lima kaki adalah 1.5 meter.
Kalau rumah saya, berhubung ada di tengah kampung, jadi susah untuk menyediakan jarak 5 kaki. Beruntung lokasi LDR ini ada jarak yang cukup lebar dari jalan raya.
Di era dimana masyarakat yang semakin lebih memikirkan uang daripada manfaat non-uang, setiap jengkal tanah harus menhasilkan uang. Sehingga trotoar pun kini didiami oleh pedagang. Padahal, jika kita mau melestarikan sejarah yang ada sejak tempo doeloe, rasanya sangat nyaman. Kita berjalan di trotoar tidak terganggu oleh pedagang atau parkir mobil.
Jasmerah bukan hanya berbicara politik. Kita memiliki sejarah peradaban yang panjang. Meski kaki lima baru muncul di masa penjajahan, tetapi tidak ada salahnya kita melestarikannya. Biarkan pejalan kaki memiliki haknya, tidak diganggu oleh kendaraan. Bagaimana di luar negeri? Karena saya belum pernah ke sana, saya tidak bisa berbicara banyak. Tetapi saya rasa banyak dari mereka yang lebih baik dalam hal mengelola trotoar.
Kaki lima, kini tinggal istilah dan nama yang kehilangan maknanya. Kaki lima adalah condoh kehidupan di masa lampau yang lebih menghargai sesama. Semoga kita tidak menghilangkan itu dan menggantinya dengan uang. :)