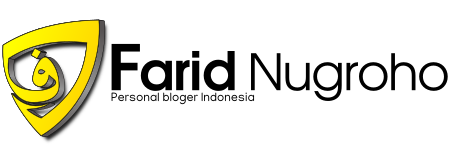Beberapa waktu terakhir banyak bermunculan komentar di lini massa terkait para pelajar atau mahasiswa banyak yang mengerjakan tugas di kafe atau kedai kopi daripada di perpustakaan. Apakah benar kedai kopi telah mengambil alih peran perpustakaan?
Fenomena ramainya kedai kopi atau kafe tidak terlepas dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Kopi bukan lagi sekadar penunda tidur tetapi ada gaya hidup di sana. Dan kesan bahwa nongkrong di warung kopi hanya dilakukan oleh orang tua, kini bisa ditepis. Didukung dengan beberapa film layar lebar yang menampilkan adegan terkait kopi semisal Ada Apa Dengan Cinta 2, Filosofi Kopi, dan lain sebagainya.
Jika dilihat face to face, tentu perpustakaan memiliki kehidupan yang berbeda dengan kedai kopi. Bahkan bisa dikatakan bahwa keduanya saling kontra. Meski saling bertolak belakang, keduanya bisa digunakan untuk tempat belajar. Meski di masa lalu belajar di kedai kopi atau kafe terlihat agak aneh. Dan kini, pertarungan antara perpustakaan dengan kedai kopi sementara dimenangkan oleh kafe. Mengapa demikian?
Banyak perpustakaan yang mati suri, demikian setidaknya jika kita tidak mau mengatakan kalau mereka hampir sebenarnya mati. Kematian perpustakaan disebabkan oleh mereka sendiri yang tidak mau berubah. Masyarakat telah berubah, kedai kopi pun berubah, tetapi perpustakaan tidak. Perpustakaan selalu dicitrakan sebagai tempat untuk mereka kutu buku. Buku dibaca dalam meja kotak, bahkan beberapa ada yang diberi sekat seperti peti mati.
Fenomena ramainya kedai kopi atau kafe tidak terlepas dengan gaya hidup masyarakat Indonesia. Kopi bukan lagi sekadar penunda tidur tetapi ada gaya hidup di sana. Dan kesan bahwa nongkrong di warung kopi hanya dilakukan oleh orang tua, kini bisa ditepis. Didukung dengan beberapa film layar lebar yang menampilkan adegan terkait kopi semisal Ada Apa Dengan Cinta 2, Filosofi Kopi, dan lain sebagainya.
Jika dilihat face to face, tentu perpustakaan memiliki kehidupan yang berbeda dengan kedai kopi. Bahkan bisa dikatakan bahwa keduanya saling kontra. Meski saling bertolak belakang, keduanya bisa digunakan untuk tempat belajar. Meski di masa lalu belajar di kedai kopi atau kafe terlihat agak aneh. Dan kini, pertarungan antara perpustakaan dengan kedai kopi sementara dimenangkan oleh kafe. Mengapa demikian?
Ada masalah di Perpustakaan
Banyak perpustakaan yang mati suri, demikian setidaknya jika kita tidak mau mengatakan kalau mereka hampir sebenarnya mati. Kematian perpustakaan disebabkan oleh mereka sendiri yang tidak mau berubah. Masyarakat telah berubah, kedai kopi pun berubah, tetapi perpustakaan tidak. Perpustakaan selalu dicitrakan sebagai tempat untuk mereka kutu buku. Buku dibaca dalam meja kotak, bahkan beberapa ada yang diberi sekat seperti peti mati.
Tidak ada peluang untuk berdiskusi di perpustakaan karena memang di perpustakaan tidak boleh membuat gaduh. Setidaknya seperti di film Ada Apa Dengan Cinta belasan tahun silam, tokoh Rangga melempar pena ke sesama pengunjung perpustakaan gegara berbincang-bincang. Hingga akhirnya perpustakaan adalah tempat seperti tempat kematian, tidak ada diskusi, tidak ada makan minum, tidak ada interaksi sosial, sekat-sekat terpapang secara eksplisit di depan mata, dan sebagainya.
Karena pada hakikatnya sifat manusia adalah dinamis dan tidak akan merasa betah ketika terlalu lama berada di tempat yang statis. Kedai kopi lah yang mengambil alih peran-peran tersebut. Di kedai kopi, para costumer bebas melakukan diskusi, makan minum sesuai dengan menu, siapapun boleh berada di sana tanpa ada kartu keanggotaan, dan lain sebagainya.
Memang ada satu yang ada di perpustakaan tetapi tidak disediakan oleh kedai kopi, yaitu ketersediaan buku. Di sisi ini yang seharusnya menjadi kekuatan pun banyak perpustakaan yang tidak bisa memanfaatkan. Banyak buku yang sudah judulnya terlalu tua dan tidak diperbaharui, tampilan yang kucel, dan hal-hal yang tidak membuat pengunjung tertarik untuk mengambil. Jika pun mengambil, mereka tidak membacanya di perpustakaan melainkan di kedai kopi. Alternatif selain meminjam buku di perpustakaan untuk kemudian dibaca di kedai kopi adalah membeli buku di toko buku karena memang lebih menjawab.
Buku pun kini banyak yang tidak lagi berbentuk buku melainkan berupa soft file atau salinan digital. Sehingga, kemana-mana tinggal membaca di gawai masing-masing baik ponsel pintar (smartphone), tablet, atau laptop. Apakah sudah banyak perpustakaan yang menyediakan jaringan wifi?
Mengapa kafe menjadi pilihan kaum milenial?
Kedai kopi bukan lagi hanya menyediakan kopi hitam. Menu-menu kekinian pun bermunculan, mulai dari kudapan hingga makanan berat. Menu utama yang banyak dicari adalah wifi. Dengan bermodal segelas kopi, maka akan diberikan password wifi yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan. Di sela-sela membaca atau mengerjakan tugas, bisa dilakukan diskusi. Ketika haus atau lapar, bisa makan sesuai pesanan. Pusing dengan kegiatan belajar, bisa berswa foto di area kedai yang instagramable dan mengunggahnya di media sosial.
Ada interaksi baik dengan sesama pengguna maupun dengan lingkungan sekitar ketika di kedai kopi. Hal yang sulit ditemukan di perpustakaan. Alih-alih interaksi, berbisik saja sudah dianggap bersuara yang mengganggu. Tampilan perpustakaan yang begitu-begitu saja rasanya tidak elok ketika dipajang di sosial media. Bahkan banyak pula perpustakaan yang tidak memiliki akun media sosial atau pun memiliki, mereka tidak menggarapnya sebagaimana sebuah perusahaan. Hasil unggahan mereka banyak yang justru menampilkan kekakuan kehidupan perpustakaan. Berbeda dengan kedai kopi, mereka justru akan senang jika banyak yang berswa foto dengan desain interior atau eksterior mereka.
 |
| Candi di tengah perpustakaan UII, menjadi daya tarik tersendiri |
Perpustakaan harus berubah
Tentu perpustakaan harus berubah dan banyak yang sudah berubah tetapi lebih banyak yang belum mau berubah. Setidaknya perpustakaan grhatama pustaka Jogja telah mengikuti perubahan tersebut. Suasana nyaman dan santai, demikian yang dicitrakan oleh perpustakaan terbesar tersebut. Spot-spot instagramable didukung dengan jaringan wifi memang mendukung aktivitas yang "anak muda banget". Tempat duduk yang santai dan beberapa titik yang bisa digunakan untuk nongkrong berdiskusi menjadi daya tarik tersendiri.
Satu kelemahan yang masih dimiliki oleh perpustakaan grhatama pustaka, sebagaimana perpustakaan-perpustakaan pada umumnya yang lain, adalah jam kunjung yang masih sangat terbatas. Jam 8.30 - 15.30 WIB, ketika perpustakaan bisa dikunjungi pada hari dan jam kerja, padahal pada jam tersebut para pelajar dan mahasiswa masih sibuk di kelas, para karyawan pun masih sibuk di tempat kerja. Ketika hendak mengunjungi perpustakaan, mereka harus menyempatkan diri, izin dari tempat belajar atau tempat kerja, atau justru malah mencuri waktu. Tentu jam yang demikian tidak efektif bagi mereka. Tetapi bagi kafe? Banyak kafe yang buka 24 jam.
Banyak tudingan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia lemah hanya gara-gara kunjungan perpustakaan rendah. Tetapi, apakah kita sudah melihat mengapa perpustakaan kurang diminati? Masyarakat tidak mau berkunjung, tetapi toh perpustakaan tidak menarik untuk dikunjungi. Di kafe justru kita melihat budaya literasi berkembang, budaya diskusi membumi, dan di toko buku masyarakat bisa mendapatkan buku yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.
Manusia adalah makhluk dinamis yang selalu berubah. Perpustakaan jika masih ingin disebut perpustakaan juga harus berubah. Perpustakaan bukan sekadar gudang buku melainkan juga menjadi tempat dimana buku itu dikupas. Setiap generasi memiliki bukunya masing-masing dan memiliki cara tersendiri bagaimana mengupasnya. Mengupas buku secara mandiri di dalam peti mati bukan lagi eranya. Kini mengupas buku adalah dengan diskusi, entah nanti sepuluh atau dua puluh tahun mendatang. Yang pasti, perpustakaan harus siap dengan perubahan yang akan hadir. Atau kah dua puluh tahun mendatang kondisi perpustakaan masih sama dengan dua puluh tahun silam? Hanya perpustakaan dan Tuhan yang tahu jawabannya.